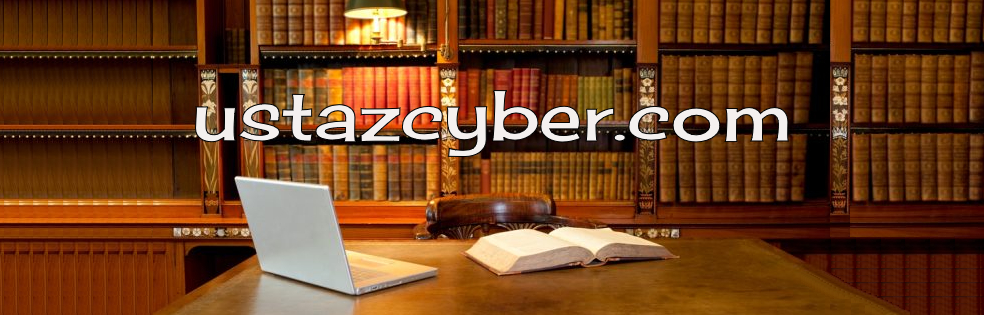main |
sidebar
ABDULLAH BIN AB.WAHAB
AKHBAR MALAYSIA
POLITIK MALAYSIA
ISLAM DI SANA SINI
Santai-santai
Blog Archive
-
▼
2015
(157)
-
▼
Ogos
(15)
- Subhanallah..Google Maps membuktikan kebenaran uca...
- Jom Buat Ubat Batuk di rumah
- Aurora dalam Al-Quran
- Ya Allah...Jadikanlah kami salah seorang daripada ...
- Rahsia Islami Untuk Jadi Macho
- Ini Dia 10 Dosa Penghambat Razeki
- “Bilakah kita boleh keluar dari Ketaatan terhadap ...
- Muslim Pencari Ridha Kaum Kuffar
- Mahar Kahwin Termahal di dunia
- Hanya Islam Membuat Hidup Bahagia
- Doa dan Ruqyah Untuk Kereta Baru
- Dr. Zakir Naik - Apa perbezaan Muslim Sunni dan Mu...
- Bakti Para Salaf pada Orangtua
- Memohon Kepada Allah Agar Mati Syahid
- Subhanallah...Inilah Kamar Tidur Mantan Amirul Muk...
-
▼
Ogos
(15)
17 Ogos 2015
“Bilakah kita boleh keluar dari Ketaatan terhadap Pemerintah ? ”
Dicatat oleh ustazcyber.com di 4:49:00 PG
KIBLAT.NET – Dalam suatu kesempatan Syaikh Abu Qatadah Al-Filistini, seorang pemerhati dunia jihad, ditanya tentang “Hukum Keluar dari Ketaatan terhadap Pemerintah”. Maka, Syaikh pun memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Secara umum, Syaikh menjelaskan bahawa “Keluar dari Ketaatan terhadap Pemerintah” itu bukan hanya berdasarkan status pemerintah yang kafir atau Muslim.
Lebih dari itu, Syaikh mengemukakan alasan-alasan yang rasional dan bernash terkait persoalan tersebut. Anda akan dapat memahami argumen yang disampaikannya hanya setelah membaca keseluruhan artikel ini. Selamat membaca!!!....
Syaikh Abu Qatadah Al-Filistini
“Kapan Keluar dari Ketaatan terhadap Pemerintah Dibolehkan”
imgid217956
Permasalahan ini termasuk kajian yang telah dipaparkan oleh para ulama salaf terdahulu. Namun, sebagian orang masih ada yang keliru dalam memahaminya, ada yang ifrat (berlebih-lebihan) dan ada juga yang tafrit (meremehkan). Sehingga untuk mengungkapkan hakikat yang sebenarnya, kajian permasalahan ini membutuhkan referensi yang lebih luas dan lengkap, tidak hanya sebatas kitab-kitab yang telah mereka tuliskan, seperti kitab Al-Ghiyats karya Al-Juwaini atau kitab Ahkamus Sulthaniah karya Al-Mawardi.
Selain itu, kita juga harus membaca pendapat-pendapat para ulama dari kalangan sahabat, tabi’in dan ulama salafus shalih, kemudian memahaminya dengan pemahaman yang benar. Keluar dari ketaatan terhadap pemimpin bukanlah perkara yang haram secara mutlak atau boleh secara mutlak. Namun dalam menghukumi status perbuatan tersebut, kita harus merinci terlebih dahulu bentuk hubungan dan status akad yang terjadi antara penguasa dengan rakyat.
Sekarang ini muncul sebagian orang yang mengkultuskan para penguasa. Mereka tidak takut kepada Allah dan bekerja untuk para thagut yang menggantikan hukum Allah SWT. Mereka menganggap bahwa penguasa selalu bersih layaknya orang yang suci. Masyarakat hari ini (sebenarnya) telah menyadari sesatnya pandangan tersebut.
Sedangkan terkait perkataan seorang penyair Muslim ketika memuji para pemimpinnya bahwa tidak ada yang dapat menduduki kekuasaan kecuali karena kekhususan yang dimiliki seseorang, dan seandainya tampuk kekuasaan itu dikasihkan kepada yang lain maka bumi ini akan bergoyang disebabkan kepemimpinan tersebut.
Maka, perkataan tersebut tentu keliru. Sebab, seseorang tidak memegang sebuah kekuasaan karena kekhususan yang dimilikinya, kemudian Allah memilihnya di antara manusia yang lain. Kadangkala, sebuah kekuasaan itu bisa juga dipegang oleh orang yang paling kufur kepada Allah SWT serta paling memusuhinya, yaitu lantaran kepiawaiannya dalam meraih hati rakyat, ia mampu menduduki sebuah kekuasaan. Seperti halnya yang difirmankan oleh Allah SWT tentang kekuasaan Fir’aun,
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
“Maka Fir‘aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.” (Az-Zukhruf 54)
Jadi –sudah seharusnya wahai saudaraku sekalian—kita menyikapi para penguasa dengan sikap yang benar sesuai dengan petunjuk sunnah yang lurus. Ini karena penguasa itu adalah bagian dari manusia, terkadang salah dan terkadang juga benar.
Perhatikan lembaran-lembaran sejarah yang telah mengajari kita tentang bagaimana cara bermuamalah dengan penguasa secara benar, serta cara yang tepat bagi seorang pemimpin dalam mengatur rakyatnya.
Lihatlah kisah para pemimpin; Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah bagian dari umat yang ketika diangkat menjadi pemimpin, mereka berdiri di atas mimbar dan berkhutbah di hadapan manusia, “Bantulah aku, karena aku membutuhkan bantuan kalian, jika kalian mendapati kesalahan dalam kepemimpinanku maka luruskanlah aku.”
Sekarang dalam bermuamalah dengan para penguasa, semua petunjuk di atas seolah hilang dari pikiran orang-orang yang mengaku dirinya Salafi. Mereka meninginkan umat ini menyikapi penguasa sebagaimana menyikapi orang-orang suci, para pemimpin itu memiliki kekhususan yang diberikan Allah untuk dikultuskan. Sehingga, beberapa di antara mereka ada yang melarang untuk membicarakan tentang kesalahan pemimpin, karena hal itu termasuk ghibah terhadap penguasa dan masuk dalam katagori dosa besar. Subhanallah!
Pemimpin adalah bagian dari umat yang dipilih untuk mengatur urusan mereka. Dia adalah pembantu bagi rakyatnya. Dia memerintah sesuai kesepakatan yang ditentukan antara dirinya dan rakyat. antara keduanya memiliki janji yang saling mengikat. Bentuk janji itulah yang akan mengikat hubungan antara pemimpin dengan rakyat yang berbaiat kepadanya. Sehingga bagi seorang pemimpin, rakyat adalah tumpuan kekuatan yang akan membantunya dalam menjalankan ketetapan-ketetapan yang mengandung maslahat bagi umat. Oleh karena itu, para ulama berkata, “Ketetapan para pemimpin itu harus sejalan dengan kemaslahatan rakyat.”
Dalam hal ini, saya ingin menjelaskan beberapa permasalahan yang berkaitan tentang status akad atau janji yang dibangun pemimpin bersama rakyat berdasarkan ketentuan akad yang menyertainya.
Rukun dalam akad sendiri adalah:
Ijab dan qobul yang menandakan keridhaan
Sesuatu yang dijanjikan (diakadkan)
Al-‘Aaqidah ( orang yang melakukan akad)
Inilah tiga rukun akad yang wajib terpenuhi. Ketika salah satu rukun tersebut dilanggar atau batal, maka rakyat boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin.
Kapan Bolehnya Seseorang Keluar dari Penguasa?
Terdapat beberapa kondisi yang membolehkan seseorang keluar dari penguasa, yaitu:
Kondisi Pertama
Imam Malik Rahimahullah pernah mengeluarkan fatwa bolehnya seseorang keluar dari ketaatan kepada Khalifah Abbasiyah. Ini karena akad yang dilakukan antara pemimpin Abbasiyah dengan umat tidak berdasarkan keridhaan bersama.
Oleh karena itu beliau berkata, “Bagi orang yang terpaksa untuk memisahkan diri darinya, ia tidak berdosa.” Hal itu menunjukkan bahwa antara pemimpin dengan rakyat tidak ada ikatan baiat. Jika tidak ada ikatan baiat, maka boleh keluar dari ketaatan kepadanya karena dia memimpin dengan cara menjajah dan memaksa rakyat untuk taat kepada pemerintah. Sehingga, hukumnya boleh bagi rakyat untuk keluar dari ketaatan kepada pengusa jika mereka berkuasa dengan cara memaksa.
Namun kemudian muncul persoalan, apakah kebolehan ini terkait erat dengan pertimbangan maslahat? Jawabannya adalah iya, harus sesuai dengan maslahat. Akan tetapi dalam hal ini kita sedang membicarakan tentang fatwa ulama salaf yang membolehkan keluar dari ketaatan kepada pemimpin jika dibentuk tidak berdasarkan keridhaan—sebagai rukun sempurnanya akad. Jika ada unsur pemaksaan maka akadnya batal, karena asas berdirinya sebuah perjanjian yang benar adalah harus didasari dengan keridhaan.
Kondisi Kedua
Kemudian kita beralih kepada rukun yang kedua, yaitu sesuatu yang dijanjikan. Atas dasar apa perjanjian yang terjalin antara rakyat dan pemimpin?
Ikatan janji tersebut dibangun atas keharusan seorang pemimpin untuk menegakkan syariat yang menjadi kewajiban bersama. Ini adalah persoalan penting, karena terkait progam yang dilakukan oleh seorang pemimpin, seperti penegakkan hudud, mengumumkan jihad, menyambut delegasi, mengatur persoalan umat dari mulai persoalan politik, sosial hingga persoalan ekonomi bangsa. Serta mengatur tegaknya kemaslahatan agama dan dunia dengan melindungi batas wilayah negara.
Inilah jenis ikatan janji yang terikat antara pemimpin dan rakyat. Jika ikatan janji tersebut tidak diwujudkan, maka umat boleh keluar dari ketaatan kepadanya. Bahkan pada taraf tertentu hukumnya menjadi wajib. Disebabkan pemimpin tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga mafsadat yang didapatkan rakyat dalam kepemimpinannya lebih besar daripada maslahat yang diinginkan.
Tugas dan kewajiban utama seorang pemimpin adalah kewajiban rakyat itu sendiri. Allah telah membebani perintah tersebut kepada umat, yaitu perintah untuk menegakkan hudud, melaksanakan jihad, menjaga perbatasan, dan menyebarkan Islam. Semua perintah tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh rakyat tanpa ada seorang pemimpin.
Karena secara tabiat manusia sipil, tidak mungkin memperbaiki kondisi manusia atau meluruskan suatu kaum kecuali dengan adanya imam. Maka, rakyatlah yang akan memilih dan menyetujui seseorang yang dapat menjalankan tugas tersebut. Kemudian atas ikatan tersebut, rakyat mengikat janji dengannya agar sama-sama dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Allah SWT berfirman,
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
Dalam ayat tersebut Allah berfirman: “Wahai para pengikut injil”. Secara redaksional, ayat tersebut tidak menyeru para penguasa, dalam artian seluruh umatlah yang dibebani untuk menegakkan hukum Allah. Namun dalam prakteknya, tidak mungkin setiap mereka menjadi qadhi. Akan tetapi harus ada seseorang dari mereka yang akan menjadi qadhi.
Harus ada seorang pemimpin yang akan mengurus persoalan jihad, karena semua perintah tersebut termasuk amal jama’i yang tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada sebuah jamaah yang mewujudkannya, tidak mungkin sebuah kumpulan dikatakan jamaah kecuali dengan adanya imam yang memimpinnya.
Jadi, beban atau kewajiban pemimpin yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka pada hakikatnya adalah kewajiban rakyat itu sendiri. Akan tetapi rakyat mengikat janji dengan pemimpinnya untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara bersamaan dan berjanji untuk tidak keluar dari kepemimpinannya.
Jika seorang pemimpin ingin mengumumkan jihad, maka siapa yang akan berjihad? Umat. Jika pemimpin ingin menegakkan hukum terhadap para pemberontak atau ingin memerangi kelompok khawarij atau juga ingin menegakkan hudud, siapa yang akan menegakkan hukum syar’i tersebut? Yang akan melaksanakannya adalah umat. Akan tetapi, umat memerlukan seorang pemimpin dan komandan.
Sama seperti shalat jamaah, seluruh umat dibebani dengan kewajiban tersebut. Namun, kewajiban menegakkan shalat jamaah tidak mungkin tegak kecuali dengan adanya seorang imam, dan imam tersebut dibebani untuk memimpin pelaksanaannya sebagaimana yang telah disepakati bersama dan berdasarkan perintah Allah SWT.
Jadi, jika seorang pemimpin berkuasa tanpa keridhaan dari umat, maka boleh keluar dari kepemimpinannya tersebut. Kebolehan tersebut tentunya juga sangat terikat dengan partimbangan maslahat. Demikianlah pendapat para salaf. Akan tetapi pertanyaannya, apakah berdosa jika keluar dari ketaatan terhadap pemimpin seperti itu?
Jawabannya tentu tidak berdosa, karena mereka ingin mengambil haknya untuk dipimpin oleh orang yang mereka ridhai. Demikian juga, seseorang tidak boleh seseorang dipaksa untuk menepati sebuah janji yang dipaksakan kepadanya. Dengan catatan, harus melihat maslahat yang akan dicapai, karena hal ini bukanlah persoalan yang menyangkut satu orang saja, namun ia adalah persoalan yang menyangkut kemaslahatan seluruh umat.
Kemudian, jika seorang pemimpin melaksanakan kewajiban yang telah dibebani oleh rakyatnya—tentunya sesuai dengan perintah Allah—maka kepemimpinan adalah miliknya sedangkan kekuasaan tetap pada rakyat, sehingga ketika pemimpin tersebut menyimpang dari kewajibannya maka rakyat pun harus bertindak.
Kita di sini tidak sedang membicarakan sosok pribadi pemimpin—apakah kafir atau tidak. Terkadang dia melaksanakan sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan umat, namun di dalamnya terdapat unsur maksiat yang sudah jelas diketahui orang, kadang juga mengandung kekufuran yang nyata, kezaliman yang merata, menyeru kepada perbuatan zina, mempermudah sarana maksiat dan memberatkan orang-orang yang taat, kadang juga melarang penyebaran agama dan mencela orang kafir, kadang ada juga yang masuk dalam kelompok orang kafir, dan ini semua adalah persoalan yang dihadapi umat. Maka saat itu, umat wajib keluar dari kepemimpinannya.
Bagaimana dengan Penguasa yang Kafir?
Pembahasan yang sering diperbincangkan oleh para ikhwan kita sekarang adalah persoalan seputar kekafiran penguasa. Apakah penguasa tersebut kafir atau tidak, harus ditinjau dari kepribadiannya. Oleh karena itu, mereka akan berkata, “Dia kan masih shalat.” Jadi saat ini saya tidak sedang membicarakan tentang status pribadi penguasa.
Namun yang saya perbincangkan adalah tentang tugas dan kewajiban dia yang telah dibebankan oleh umat. Maka, saat itu umat wajib keluar dari kepemimpinannya jika pemimpin tersebut menyebarkan kezaliman dan tidak mewujudkan sejumlah janji yang telah disepakatinya.
Sesuai dengan maksud hadits, “Kecuali jika kamu melihat kemaksiatan secara terang-terangan.”
Nabi SAW bersabda, “Kecuali jika kalian melihat.” Lafadz ini menunjukkan jika kita melihat maksiat secara nyata yang berkaitan dengan persoalan umat, maka kewajiban umat adalah keluar dari kepemimpinannya. Karena ketika itu, dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan tujuan kepemimpinan.
Meskipun pada awalnya dia masih menegakkan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, namun belakangan dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban tersebut. Maka, saat itulah umat boleh keluar dari kepemimpinannya tersebut, baik statusnya sudah dikafirkan ataupun tidak.
Jadi yang kita katakan dalam poin ini adalah kapan ikatan janji antara rakyat dengan pengusa itu batal.
Tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang tidak berhukum dengan syariat Allah maka dia kafir, sebagaimana firman Allah SWT,
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir.” (Al-Maidah: 44)
Akan tetapi, terkadang maksiat yang dilakukannya tidak sampai pada taraf kekafiran. seperti berbuat zalim terhadap rakyat, menyerahkan wilayah kekuasaan kepada para pencuri, pembunuh dan orang-orang kafir. Iya, terkadang tindakan tersebut tidak menyebabkan dia menjadi kafir. Tetapi dalam hal ini, dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang telah terikat dalam ikatan janji, dan dengan janji tersebut kita selaku umat mengangkatnya sebagai pemimpin.
Kondisi Ketiga
Dilihat dari sisi pihak yang melaksanakan akad, dalam hal ini kita sedang membahas persoalan terkait pemimpin, bukan rakyat. Karena status rakyat ketika ada yang membatalkan janji yang telah diikrarkannya kepada seorang pemimpin –seperti melakukan kekufuran, memberontak atau keluar dari ketaatan kepada pemimpin, maka kewajiban pemimpin saat itu adalah mengatasinya dengan menegakkan hudud kepada orang tersebut. Begitu pula ketika ada yang memberontak, melakukan kezaliman atau merusak baiat dengan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat atau sengaja membatalkan baiat tersebut.
Sekarang ini yang kita bicarakan adalah tentang status pemimpin. Perhatikan pendapat para ulama seputar status pemimpin dalam kitab Siyasah Syar’iyah. Mereka berkata, “Jika salah seorang pemimpin mengalami kecelakaan maka dia harus dilengserkan, yaitu jika dia tertimpa kecelakaan seperti buta maka harus dilengserkan. Kenapa? Karena dengan kecelakaan tersebut—tidak ada dalil tentang hal ini—dia tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin.”
Sekarang kita lihat status akad! Siapa saja yang melakukan sebuah akad, maka dia harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan janji yang terkandung dalam akad tersebut. Misalnya seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang shalihah, ahli ibadah dan selalu menjaga dirinya namun dia tidak mampu mewujudkan kandungan ikrar janji yang dilafadzkannya—yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada laki-laki tersebut—maka meskipun pada saat itu dia seorang yang ahli ibadah yang shalihah, laki-laki tersebut tetap dibolehkan untuk membatalkan akadnya. Pada saat itu akad yang dibatalkan bukan atas dasar karena perempuan itu kafir, bukan juga karena dia fasik, namun dia membatalkan akad tersebut karena perempuan itu tidak mampu mewujudkan kandungan janji yang diikrarkannya.
Wahai sekalian manusia, wahai umat Muhammad SAW… Apakah akad yang dilakukan oleh seorang imam itu lebih rendah kedudukannya daripada akad perempuan di atas? Akad perempuan di atas hanya berefek buruk pada diri dan keluarganya semata, sedangkan akad kepemimpinan dapat merusak umat seluruhnya.
Ketiga poin di atas terkait dengan bolehnya keluar dari pemimpin ditinjau dari sisi pihak yang melakukan akad. Yaitu, manakala seorang pemimpin tidak mampu mewujudkan tugasnya atau mengalami musibah sehingga dapat menghalanginya untuk melakukan kewajiban.
Berkenaan dengan redaksi hadits “Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata”, para ulama berkata, “yaitu jika status pemimpin telah menjadi kafir.” Dalam hal ini saya tidak berbicara tentang kekafiran penguasa karena tidak melakukan kewajiban kepemimpinannya. Akan tetapi saya sedang membicarakan tentang status pemimpin itu sendiri.
Kemudian apakah ketika pemimpin berbuat fasik, minum khamer, melakukan zina, melakukan kezaliman dengan tangannya sendiri namun tidak mengajak orang lain untuk menirunya, apakah lantas rakyat boleh keluar dari ketaatan kepadanya atau tidak? Permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah.
Jadi, pernyataan yang memastikan bahwa Ahlus Sunnah tidak membolehkan keluar dari ketaatatan kepada pemimpin secara mutlak adalah pernyataan batil. Bagaimana dengan sikap keluarnya Husain bin Ali RA, terus bagaimana dengan sikap Abdullah bin Zubair yang keluar dari dari kepemimpinan saat itu. Hal tersebut tidak lain karena mereka mendapati kefasikan dan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa.
Kemudian jumhur ulama Ahlus Sunnah telah menetapkan dalam fatwa mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Atsqalani dalam Fathul Bari, bahwa setelah terjadinya peristiwa Hurrah, kezaliman Yazid bin Muawiyah, peristiwa Dier Jamajim, dan setelah pembantaian terhadap para ulama yang dilakukan oleh Hajjaj dan ketika itu yang menjadi pemimpin ulama adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Asy’ats, maka mulai saat itu Ahlus Sunnah berubah pendapatnya, sehingga mereka membolehkan keluar dari ketaatan kepada pemimpin.
Maka pendapat ulama ahlus sunnah dalam menilai pemimpin yang fasik—bukan pemimpin yang tidak menegakkan hukum syar’i dan beban yang terkandung dalam janji yang diikrarkannya—berubah menjadi “kapan seseorang harus menaati pemimpin dan kapan boleh keluar dari kepemimpinan tersebut”. Namun sangat disayangkan ketika ada sebagian orang yang mengatakan “tidak boleh”. Maka, perhatikanlah besarnya mafsadat dari perkataan tersebut!
Akad atau janji yang paling agung adalah janji antara rakyat dan pemimpin. Oleh karena itu, berkhianat dalam hal ini termasuk dosa yang paling besar. Akad tersebut tidak boleh dibatalkan kecuali ada pembatal syar’I di dalamnya. Artinya jika sebuah akad telah terjalin antara rakyat dengan pemimpin, maka rakyat tidak boleh membatalkannya kecuali terdapat ketentuaan syar’i yang membatalkan akad tersebut.
Rakyat memiliki hak untuk memilih siapa yang akan dijadikan pemimpin, mereka wajib memilih pemimpin dari orang yang paling mulia di antara mereka, memiliki kekuatan serta integritas yang tinggi. Jika kemudian hari janji tersebut batal karena faktor syar’I, maka rakyat boleh mencopot kedudukannya. Seperti ketika tidak terjalinnya akad dengan benar, pemimpin tidak mampu mewujudkan tujuan dan tugas dari kepemimpinannya, atau seorang pemimpin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan janji yang telah diikrarkannya.
Kemudian pada saat ini muncul sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak boleh keluar dari penguasa kecuali jika dia kafir, sebab kekafirannya bukan karena tidak melakukan tugas kepemimpinan namun karena kekafiran personal dirinya.
Tidak boleh keluar dari ketaatan kepda pemimpin meskipun dia menyebarkan kezaliman, menghilangkan jihad, berhukum dengan selain hukum Allah, dan berlaku sewenang-wenang terhadap umat. Saat ini para pemimpin menjual negara, rakyat dan kehormatannya kepada orang-orang kafir, dan menjadi pengikut orang kafir. Lantas kemudian orang-orang tersebut berkata, tidak boleh keluar dari kepemimpinan mereka kecuali jika mereka telah kafir! Lalu bagaimana mereka bisa kafir? Orang-orang itu akan berkata, “Pemimpin dikafirkan jika dirinya melakukan kekufuran yang nyata.”
Oleh karena itulah mereka sering berkata, “Pemimpin itu kan masih shalat. Ingat! persoalan janji, persoalan hukum itu tidak masuk dalam persoalan shalat yang dia lakukan! Namun lebih kepada faktor kepemimpinannya, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam bagian yang ketiga—dari segi pelaku yang melakukan akad.
Kita berbicara tentang hukum dan tugas pemimpin yang berhubungan dengan akad yang mengesahkan kepemimpinnannya. Mereka berkata, “Tidak boleh memberontak pemimpin kecuali jika status pribadi mereka telah kafir.” Jadi, meskipun dia membatalkan seluruh janji yang terkait dengan kepemimpinannya, selama dia tidak kafir maka tidak boleh keluar dari ketaatan kepdanya.
Kemudian mereka berkata, bukan hak kita untuk mengafirkan penguasa. Salah satu catatan atas kerancuan berpikir mereka atas sesuatu yang tidak mungkin terjadi: kita tidak boleh mengafirkan pemimpin sampai kita mengetahui isi hatinya, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin kecuali jika dia kafir, kita tidak boleh mengafirkannya sehingga kita bisa memastikan isi hatinya, apakah hatinya mengingkari perbuatan kufurnya atau tidak.
Artinya jika dia melakukan perbuatan kufur akbar dengan perbuatan yang telah disebutkan kafir oleh Allah; seperti berhukum dengan selain hukum Allah, mencela agama Islam seperti menghina sunnah, maka mereka akan berkata, “Pelaku tersebut tidak boleh kita hukumi kafir sehingga kita bisa mengetahui isi hatinya, apakah dia menghalalkan perbuatan tersebut ataukah tidak.”
Maka pada hakikatnya sikap seperti itu sama saja menghilangkan makna hadits Nabi SAW, “Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata.” Tidak mungkin kita menilai sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang nampak saja. Kemudian mengapa kita dituntut atau mereka menuntut umat agar tidak mengafirkan pemimpin atau keluar dari ketaatan kepadanya kecuali setelah dia mengetahui isi hatinya???
Para penguasa itu telah mengetahui permainan ini, mereka melakukan setiap perbuatan kufur—kekufuran yang telah ditetapkan Allah SWT—kemudian dia tampil di depan rakyatnya dan berkata, “Kami bagian dari kaum muslimin.”. Saat itulah (menjadi alasan) tidak boleh keluar dari kepemimpinannya. Sudah sewajarnya jika ada anggapan agama Yahudi, Nasrani dan konsep sekuler dalam berpolitik menjadi lebih mulia dan terhormat daripada agama Islam yang mereka yakini.
Akad yang paling besar dan berkaitan dengan kepentingan Islam adalah menyebarkan agama, menegakkan kebenaran, keadilan dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Inilah janji utama antara pemimpin dan rakyat.
Sehingga dalam hal ini, persoalan utama yang seharusnya ditinjau dari bentuk janji utama tersebut diganti menjadi kepada persoalan pribadi pemimpin. Sementara kita tidak mungkin menghukuminya kecuali setelah mengetahui isi hatinya. Sehingga kita membutuhkan alat deteksi hati yang paling canggih dan tentu alat itu tidak akan ada. Yah, alat untuk mengetahui isi hati, apakah dia menghalalkan sebuah perbuatan atau tidak, apakah dia mencintai Islam atau benci terhadapnya.
Penguasa mengerti bahwa umat ini tidak tahu tentang akad, tidak tahu makna hukum, tidak mengerti hakikat pemimpin. Kondisi seperti ini menjadikan para penguasa bisa dengan leluasa memperlakukan umat yang telah terdokrin dengan pemikiran di atas. Dia akan tampil di hadapan mereka dan berkata, “Kami Ahlus Sunnah, kita beragama Islam, kita mencintai Islam, kita ingin Islam ini bisa berkembang dan meluas.” Setelah itu, selesailah semua urusan!
Maka sangat wajar jika realitas yang terjadi sekarang ini umat Islam menjadi umat yang paling hina, sedangkan thaghut yang paling besar saat ini adalah para pengusa kaum muslimin yang bisa bertindak dengan sekehendaknya sendiri.
Bandingkan dengan negara Barat, apakah ada pemimpin mereka yang bisa bertindak sekehendaknya sendiri seperti halnya para pemimpin di negara kita? Pemimpin yang bisa mengeksploitasi rakyat sehendaknya sendiri dan bebas menzalimi mereka, sementara rakyat tidak mau peduli apa yang dilakukan pemimpinnya, karena mereka tidak boleh mempertanyakan kelakuan para pemimpinnya, selain pertanyaan itu juga berpotensi munculnya kebencian di hati rakyat—hasbunallahu wa ni’mal wakiil.
Sekarang para pemimpin bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, sedangkan kita tidak boleh keluar dari kepemimpinan tersebut sampai dia menjadi kafir. Terus kita tidak boleh mengafirkan mereka sampai kita bisa menelisik isi hati mereka. Sementara itu Nabi SAW bersabda, “Kecuali jika kamu melihat kekufuran yang nyata.” Lantas, bagaimana bisa kita melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, bagaimana kita bisa melihat isi hati seseorang?!
Jadi, kapan kita boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin?
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam hal ini kita harus melihat status akad yang terjalin antara rakyat dan pemimpin dengan benar dan sesuai petunjuk syar’i. Kita harus menilai berdsasrkan petunjuk agama Allah SWT dan jauh dari sikap pengagungan atau pengkultusan terhadap para pemimpin seperti yang telah terjadi hari ini.
Kita harus menjelaskan kepada umat bahwa kewajiban yang dibebankan kepada pemimpin itu adalah sama dengan kewajiban yang dibebankan kepada umat. Akan tetapi umat mengangkatnya sebagai pemimpin agar bisa menuntun mereka untuk merealisasikan kewajiban tersebut. Demikianlah gambaran hubungan yang sebenarnya antara hukum, pemimpin dan yang dipimpin di dalam Islam. Atas dasar itu pula kita juga bisa mengerti kapan seseorang boleh keluar dari ketaatan kepada penguasa.
Kapan Wajibnya Keluar dari Ketaatan terhadap Pemimpin yang Melakukan Kekufuran?
Pertama
Menurut ijmak para ulama, rakyat wajib keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya jika pemimpin tersebut kafir. Maknanya bahwa jika dia melakukan salah satu perbuatan kekufuran, maka rakyat boleh keluar dari kepemimpinannya tanpa harus melihat isi hatinya, tanpa harus melihat niatnya, tanpa harus melihat maksudnya –apakah dia mengingkarinya atau tidak. Namun perintahya adalah, “Kecuali jika kamu melihat kekufuran yang nyata”, yaitu jika pemimpin tersebut melakukan perbuatan kufur, baik perbuatan kufur yang bersifat pribadi seperti menghina agama, menginjak Al-Qur’an atau perbuatan kufur yang berkaitan dengan rakyat.
Kedua
Wajib keluar dari ketaatan kepada pemimpin ketika pemimpin tersebut meninggalkan tugas utama dari kepemimpinan; seperti tugas menegakkan syariat, menegakkan keadilan, menyebarkan Islam dengan syariat jihad fi sabilillah. Apabila seorang pemimpin mengabaikan salah satu dari urasan utama yang dipercayakan umat kepadanya, maka umat tersebut wajib keluar dari kepemimpinannya.
Penerjemah: Fahrudin
Lebih dari itu, Syaikh mengemukakan alasan-alasan yang rasional dan bernash terkait persoalan tersebut. Anda akan dapat memahami argumen yang disampaikannya hanya setelah membaca keseluruhan artikel ini. Selamat membaca!!!....
Syaikh Abu Qatadah Al-Filistini
“Kapan Keluar dari Ketaatan terhadap Pemerintah Dibolehkan”
imgid217956
Permasalahan ini termasuk kajian yang telah dipaparkan oleh para ulama salaf terdahulu. Namun, sebagian orang masih ada yang keliru dalam memahaminya, ada yang ifrat (berlebih-lebihan) dan ada juga yang tafrit (meremehkan). Sehingga untuk mengungkapkan hakikat yang sebenarnya, kajian permasalahan ini membutuhkan referensi yang lebih luas dan lengkap, tidak hanya sebatas kitab-kitab yang telah mereka tuliskan, seperti kitab Al-Ghiyats karya Al-Juwaini atau kitab Ahkamus Sulthaniah karya Al-Mawardi.
Selain itu, kita juga harus membaca pendapat-pendapat para ulama dari kalangan sahabat, tabi’in dan ulama salafus shalih, kemudian memahaminya dengan pemahaman yang benar. Keluar dari ketaatan terhadap pemimpin bukanlah perkara yang haram secara mutlak atau boleh secara mutlak. Namun dalam menghukumi status perbuatan tersebut, kita harus merinci terlebih dahulu bentuk hubungan dan status akad yang terjadi antara penguasa dengan rakyat.
Sekarang ini muncul sebagian orang yang mengkultuskan para penguasa. Mereka tidak takut kepada Allah dan bekerja untuk para thagut yang menggantikan hukum Allah SWT. Mereka menganggap bahwa penguasa selalu bersih layaknya orang yang suci. Masyarakat hari ini (sebenarnya) telah menyadari sesatnya pandangan tersebut.
Sedangkan terkait perkataan seorang penyair Muslim ketika memuji para pemimpinnya bahwa tidak ada yang dapat menduduki kekuasaan kecuali karena kekhususan yang dimiliki seseorang, dan seandainya tampuk kekuasaan itu dikasihkan kepada yang lain maka bumi ini akan bergoyang disebabkan kepemimpinan tersebut.
Maka, perkataan tersebut tentu keliru. Sebab, seseorang tidak memegang sebuah kekuasaan karena kekhususan yang dimilikinya, kemudian Allah memilihnya di antara manusia yang lain. Kadangkala, sebuah kekuasaan itu bisa juga dipegang oleh orang yang paling kufur kepada Allah SWT serta paling memusuhinya, yaitu lantaran kepiawaiannya dalam meraih hati rakyat, ia mampu menduduki sebuah kekuasaan. Seperti halnya yang difirmankan oleh Allah SWT tentang kekuasaan Fir’aun,
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
“Maka Fir‘aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.” (Az-Zukhruf 54)
Jadi –sudah seharusnya wahai saudaraku sekalian—kita menyikapi para penguasa dengan sikap yang benar sesuai dengan petunjuk sunnah yang lurus. Ini karena penguasa itu adalah bagian dari manusia, terkadang salah dan terkadang juga benar.
Perhatikan lembaran-lembaran sejarah yang telah mengajari kita tentang bagaimana cara bermuamalah dengan penguasa secara benar, serta cara yang tepat bagi seorang pemimpin dalam mengatur rakyatnya.
Lihatlah kisah para pemimpin; Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah bagian dari umat yang ketika diangkat menjadi pemimpin, mereka berdiri di atas mimbar dan berkhutbah di hadapan manusia, “Bantulah aku, karena aku membutuhkan bantuan kalian, jika kalian mendapati kesalahan dalam kepemimpinanku maka luruskanlah aku.”
Sekarang dalam bermuamalah dengan para penguasa, semua petunjuk di atas seolah hilang dari pikiran orang-orang yang mengaku dirinya Salafi. Mereka meninginkan umat ini menyikapi penguasa sebagaimana menyikapi orang-orang suci, para pemimpin itu memiliki kekhususan yang diberikan Allah untuk dikultuskan. Sehingga, beberapa di antara mereka ada yang melarang untuk membicarakan tentang kesalahan pemimpin, karena hal itu termasuk ghibah terhadap penguasa dan masuk dalam katagori dosa besar. Subhanallah!
Pemimpin adalah bagian dari umat yang dipilih untuk mengatur urusan mereka. Dia adalah pembantu bagi rakyatnya. Dia memerintah sesuai kesepakatan yang ditentukan antara dirinya dan rakyat. antara keduanya memiliki janji yang saling mengikat. Bentuk janji itulah yang akan mengikat hubungan antara pemimpin dengan rakyat yang berbaiat kepadanya. Sehingga bagi seorang pemimpin, rakyat adalah tumpuan kekuatan yang akan membantunya dalam menjalankan ketetapan-ketetapan yang mengandung maslahat bagi umat. Oleh karena itu, para ulama berkata, “Ketetapan para pemimpin itu harus sejalan dengan kemaslahatan rakyat.”
Dalam hal ini, saya ingin menjelaskan beberapa permasalahan yang berkaitan tentang status akad atau janji yang dibangun pemimpin bersama rakyat berdasarkan ketentuan akad yang menyertainya.
Rukun dalam akad sendiri adalah:
Ijab dan qobul yang menandakan keridhaan
Sesuatu yang dijanjikan (diakadkan)
Al-‘Aaqidah ( orang yang melakukan akad)
Inilah tiga rukun akad yang wajib terpenuhi. Ketika salah satu rukun tersebut dilanggar atau batal, maka rakyat boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin.
Kapan Bolehnya Seseorang Keluar dari Penguasa?
Terdapat beberapa kondisi yang membolehkan seseorang keluar dari penguasa, yaitu:
Kondisi Pertama
Imam Malik Rahimahullah pernah mengeluarkan fatwa bolehnya seseorang keluar dari ketaatan kepada Khalifah Abbasiyah. Ini karena akad yang dilakukan antara pemimpin Abbasiyah dengan umat tidak berdasarkan keridhaan bersama.
Oleh karena itu beliau berkata, “Bagi orang yang terpaksa untuk memisahkan diri darinya, ia tidak berdosa.” Hal itu menunjukkan bahwa antara pemimpin dengan rakyat tidak ada ikatan baiat. Jika tidak ada ikatan baiat, maka boleh keluar dari ketaatan kepadanya karena dia memimpin dengan cara menjajah dan memaksa rakyat untuk taat kepada pemerintah. Sehingga, hukumnya boleh bagi rakyat untuk keluar dari ketaatan kepada pengusa jika mereka berkuasa dengan cara memaksa.
Namun kemudian muncul persoalan, apakah kebolehan ini terkait erat dengan pertimbangan maslahat? Jawabannya adalah iya, harus sesuai dengan maslahat. Akan tetapi dalam hal ini kita sedang membicarakan tentang fatwa ulama salaf yang membolehkan keluar dari ketaatan kepada pemimpin jika dibentuk tidak berdasarkan keridhaan—sebagai rukun sempurnanya akad. Jika ada unsur pemaksaan maka akadnya batal, karena asas berdirinya sebuah perjanjian yang benar adalah harus didasari dengan keridhaan.
Kondisi Kedua
Kemudian kita beralih kepada rukun yang kedua, yaitu sesuatu yang dijanjikan. Atas dasar apa perjanjian yang terjalin antara rakyat dan pemimpin?
Ikatan janji tersebut dibangun atas keharusan seorang pemimpin untuk menegakkan syariat yang menjadi kewajiban bersama. Ini adalah persoalan penting, karena terkait progam yang dilakukan oleh seorang pemimpin, seperti penegakkan hudud, mengumumkan jihad, menyambut delegasi, mengatur persoalan umat dari mulai persoalan politik, sosial hingga persoalan ekonomi bangsa. Serta mengatur tegaknya kemaslahatan agama dan dunia dengan melindungi batas wilayah negara.
Inilah jenis ikatan janji yang terikat antara pemimpin dan rakyat. Jika ikatan janji tersebut tidak diwujudkan, maka umat boleh keluar dari ketaatan kepadanya. Bahkan pada taraf tertentu hukumnya menjadi wajib. Disebabkan pemimpin tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga mafsadat yang didapatkan rakyat dalam kepemimpinannya lebih besar daripada maslahat yang diinginkan.
Tugas dan kewajiban utama seorang pemimpin adalah kewajiban rakyat itu sendiri. Allah telah membebani perintah tersebut kepada umat, yaitu perintah untuk menegakkan hudud, melaksanakan jihad, menjaga perbatasan, dan menyebarkan Islam. Semua perintah tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh rakyat tanpa ada seorang pemimpin.
Karena secara tabiat manusia sipil, tidak mungkin memperbaiki kondisi manusia atau meluruskan suatu kaum kecuali dengan adanya imam. Maka, rakyatlah yang akan memilih dan menyetujui seseorang yang dapat menjalankan tugas tersebut. Kemudian atas ikatan tersebut, rakyat mengikat janji dengannya agar sama-sama dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Allah SWT berfirman,
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
Dalam ayat tersebut Allah berfirman: “Wahai para pengikut injil”. Secara redaksional, ayat tersebut tidak menyeru para penguasa, dalam artian seluruh umatlah yang dibebani untuk menegakkan hukum Allah. Namun dalam prakteknya, tidak mungkin setiap mereka menjadi qadhi. Akan tetapi harus ada seseorang dari mereka yang akan menjadi qadhi.
Harus ada seorang pemimpin yang akan mengurus persoalan jihad, karena semua perintah tersebut termasuk amal jama’i yang tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada sebuah jamaah yang mewujudkannya, tidak mungkin sebuah kumpulan dikatakan jamaah kecuali dengan adanya imam yang memimpinnya.
Jadi, beban atau kewajiban pemimpin yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka pada hakikatnya adalah kewajiban rakyat itu sendiri. Akan tetapi rakyat mengikat janji dengan pemimpinnya untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara bersamaan dan berjanji untuk tidak keluar dari kepemimpinannya.
Jika seorang pemimpin ingin mengumumkan jihad, maka siapa yang akan berjihad? Umat. Jika pemimpin ingin menegakkan hukum terhadap para pemberontak atau ingin memerangi kelompok khawarij atau juga ingin menegakkan hudud, siapa yang akan menegakkan hukum syar’i tersebut? Yang akan melaksanakannya adalah umat. Akan tetapi, umat memerlukan seorang pemimpin dan komandan.
Sama seperti shalat jamaah, seluruh umat dibebani dengan kewajiban tersebut. Namun, kewajiban menegakkan shalat jamaah tidak mungkin tegak kecuali dengan adanya seorang imam, dan imam tersebut dibebani untuk memimpin pelaksanaannya sebagaimana yang telah disepakati bersama dan berdasarkan perintah Allah SWT.
Jadi, jika seorang pemimpin berkuasa tanpa keridhaan dari umat, maka boleh keluar dari kepemimpinannya tersebut. Kebolehan tersebut tentunya juga sangat terikat dengan partimbangan maslahat. Demikianlah pendapat para salaf. Akan tetapi pertanyaannya, apakah berdosa jika keluar dari ketaatan terhadap pemimpin seperti itu?
Jawabannya tentu tidak berdosa, karena mereka ingin mengambil haknya untuk dipimpin oleh orang yang mereka ridhai. Demikian juga, seseorang tidak boleh seseorang dipaksa untuk menepati sebuah janji yang dipaksakan kepadanya. Dengan catatan, harus melihat maslahat yang akan dicapai, karena hal ini bukanlah persoalan yang menyangkut satu orang saja, namun ia adalah persoalan yang menyangkut kemaslahatan seluruh umat.
Kemudian, jika seorang pemimpin melaksanakan kewajiban yang telah dibebani oleh rakyatnya—tentunya sesuai dengan perintah Allah—maka kepemimpinan adalah miliknya sedangkan kekuasaan tetap pada rakyat, sehingga ketika pemimpin tersebut menyimpang dari kewajibannya maka rakyat pun harus bertindak.
Kita di sini tidak sedang membicarakan sosok pribadi pemimpin—apakah kafir atau tidak. Terkadang dia melaksanakan sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan umat, namun di dalamnya terdapat unsur maksiat yang sudah jelas diketahui orang, kadang juga mengandung kekufuran yang nyata, kezaliman yang merata, menyeru kepada perbuatan zina, mempermudah sarana maksiat dan memberatkan orang-orang yang taat, kadang juga melarang penyebaran agama dan mencela orang kafir, kadang ada juga yang masuk dalam kelompok orang kafir, dan ini semua adalah persoalan yang dihadapi umat. Maka saat itu, umat wajib keluar dari kepemimpinannya.
Bagaimana dengan Penguasa yang Kafir?
Pembahasan yang sering diperbincangkan oleh para ikhwan kita sekarang adalah persoalan seputar kekafiran penguasa. Apakah penguasa tersebut kafir atau tidak, harus ditinjau dari kepribadiannya. Oleh karena itu, mereka akan berkata, “Dia kan masih shalat.” Jadi saat ini saya tidak sedang membicarakan tentang status pribadi penguasa.
Namun yang saya perbincangkan adalah tentang tugas dan kewajiban dia yang telah dibebankan oleh umat. Maka, saat itu umat wajib keluar dari kepemimpinannya jika pemimpin tersebut menyebarkan kezaliman dan tidak mewujudkan sejumlah janji yang telah disepakatinya.
Sesuai dengan maksud hadits, “Kecuali jika kamu melihat kemaksiatan secara terang-terangan.”
Nabi SAW bersabda, “Kecuali jika kalian melihat.” Lafadz ini menunjukkan jika kita melihat maksiat secara nyata yang berkaitan dengan persoalan umat, maka kewajiban umat adalah keluar dari kepemimpinannya. Karena ketika itu, dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan tujuan kepemimpinan.
Meskipun pada awalnya dia masih menegakkan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, namun belakangan dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban tersebut. Maka, saat itulah umat boleh keluar dari kepemimpinannya tersebut, baik statusnya sudah dikafirkan ataupun tidak.
Jadi yang kita katakan dalam poin ini adalah kapan ikatan janji antara rakyat dengan pengusa itu batal.
Tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang tidak berhukum dengan syariat Allah maka dia kafir, sebagaimana firman Allah SWT,
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir.” (Al-Maidah: 44)
Akan tetapi, terkadang maksiat yang dilakukannya tidak sampai pada taraf kekafiran. seperti berbuat zalim terhadap rakyat, menyerahkan wilayah kekuasaan kepada para pencuri, pembunuh dan orang-orang kafir. Iya, terkadang tindakan tersebut tidak menyebabkan dia menjadi kafir. Tetapi dalam hal ini, dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang telah terikat dalam ikatan janji, dan dengan janji tersebut kita selaku umat mengangkatnya sebagai pemimpin.
Kondisi Ketiga
Dilihat dari sisi pihak yang melaksanakan akad, dalam hal ini kita sedang membahas persoalan terkait pemimpin, bukan rakyat. Karena status rakyat ketika ada yang membatalkan janji yang telah diikrarkannya kepada seorang pemimpin –seperti melakukan kekufuran, memberontak atau keluar dari ketaatan kepada pemimpin, maka kewajiban pemimpin saat itu adalah mengatasinya dengan menegakkan hudud kepada orang tersebut. Begitu pula ketika ada yang memberontak, melakukan kezaliman atau merusak baiat dengan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat atau sengaja membatalkan baiat tersebut.
Sekarang ini yang kita bicarakan adalah tentang status pemimpin. Perhatikan pendapat para ulama seputar status pemimpin dalam kitab Siyasah Syar’iyah. Mereka berkata, “Jika salah seorang pemimpin mengalami kecelakaan maka dia harus dilengserkan, yaitu jika dia tertimpa kecelakaan seperti buta maka harus dilengserkan. Kenapa? Karena dengan kecelakaan tersebut—tidak ada dalil tentang hal ini—dia tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin.”
Sekarang kita lihat status akad! Siapa saja yang melakukan sebuah akad, maka dia harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan janji yang terkandung dalam akad tersebut. Misalnya seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang shalihah, ahli ibadah dan selalu menjaga dirinya namun dia tidak mampu mewujudkan kandungan ikrar janji yang dilafadzkannya—yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada laki-laki tersebut—maka meskipun pada saat itu dia seorang yang ahli ibadah yang shalihah, laki-laki tersebut tetap dibolehkan untuk membatalkan akadnya. Pada saat itu akad yang dibatalkan bukan atas dasar karena perempuan itu kafir, bukan juga karena dia fasik, namun dia membatalkan akad tersebut karena perempuan itu tidak mampu mewujudkan kandungan janji yang diikrarkannya.
Wahai sekalian manusia, wahai umat Muhammad SAW… Apakah akad yang dilakukan oleh seorang imam itu lebih rendah kedudukannya daripada akad perempuan di atas? Akad perempuan di atas hanya berefek buruk pada diri dan keluarganya semata, sedangkan akad kepemimpinan dapat merusak umat seluruhnya.
Ketiga poin di atas terkait dengan bolehnya keluar dari pemimpin ditinjau dari sisi pihak yang melakukan akad. Yaitu, manakala seorang pemimpin tidak mampu mewujudkan tugasnya atau mengalami musibah sehingga dapat menghalanginya untuk melakukan kewajiban.
Berkenaan dengan redaksi hadits “Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata”, para ulama berkata, “yaitu jika status pemimpin telah menjadi kafir.” Dalam hal ini saya tidak berbicara tentang kekafiran penguasa karena tidak melakukan kewajiban kepemimpinannya. Akan tetapi saya sedang membicarakan tentang status pemimpin itu sendiri.
Kemudian apakah ketika pemimpin berbuat fasik, minum khamer, melakukan zina, melakukan kezaliman dengan tangannya sendiri namun tidak mengajak orang lain untuk menirunya, apakah lantas rakyat boleh keluar dari ketaatan kepadanya atau tidak? Permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah.
Jadi, pernyataan yang memastikan bahwa Ahlus Sunnah tidak membolehkan keluar dari ketaatatan kepada pemimpin secara mutlak adalah pernyataan batil. Bagaimana dengan sikap keluarnya Husain bin Ali RA, terus bagaimana dengan sikap Abdullah bin Zubair yang keluar dari dari kepemimpinan saat itu. Hal tersebut tidak lain karena mereka mendapati kefasikan dan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa.
Kemudian jumhur ulama Ahlus Sunnah telah menetapkan dalam fatwa mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Atsqalani dalam Fathul Bari, bahwa setelah terjadinya peristiwa Hurrah, kezaliman Yazid bin Muawiyah, peristiwa Dier Jamajim, dan setelah pembantaian terhadap para ulama yang dilakukan oleh Hajjaj dan ketika itu yang menjadi pemimpin ulama adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Asy’ats, maka mulai saat itu Ahlus Sunnah berubah pendapatnya, sehingga mereka membolehkan keluar dari ketaatan kepada pemimpin.
Maka pendapat ulama ahlus sunnah dalam menilai pemimpin yang fasik—bukan pemimpin yang tidak menegakkan hukum syar’i dan beban yang terkandung dalam janji yang diikrarkannya—berubah menjadi “kapan seseorang harus menaati pemimpin dan kapan boleh keluar dari kepemimpinan tersebut”. Namun sangat disayangkan ketika ada sebagian orang yang mengatakan “tidak boleh”. Maka, perhatikanlah besarnya mafsadat dari perkataan tersebut!
Akad atau janji yang paling agung adalah janji antara rakyat dan pemimpin. Oleh karena itu, berkhianat dalam hal ini termasuk dosa yang paling besar. Akad tersebut tidak boleh dibatalkan kecuali ada pembatal syar’I di dalamnya. Artinya jika sebuah akad telah terjalin antara rakyat dengan pemimpin, maka rakyat tidak boleh membatalkannya kecuali terdapat ketentuaan syar’i yang membatalkan akad tersebut.
Rakyat memiliki hak untuk memilih siapa yang akan dijadikan pemimpin, mereka wajib memilih pemimpin dari orang yang paling mulia di antara mereka, memiliki kekuatan serta integritas yang tinggi. Jika kemudian hari janji tersebut batal karena faktor syar’I, maka rakyat boleh mencopot kedudukannya. Seperti ketika tidak terjalinnya akad dengan benar, pemimpin tidak mampu mewujudkan tujuan dan tugas dari kepemimpinannya, atau seorang pemimpin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan janji yang telah diikrarkannya.
Kemudian pada saat ini muncul sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak boleh keluar dari penguasa kecuali jika dia kafir, sebab kekafirannya bukan karena tidak melakukan tugas kepemimpinan namun karena kekafiran personal dirinya.
Tidak boleh keluar dari ketaatan kepda pemimpin meskipun dia menyebarkan kezaliman, menghilangkan jihad, berhukum dengan selain hukum Allah, dan berlaku sewenang-wenang terhadap umat. Saat ini para pemimpin menjual negara, rakyat dan kehormatannya kepada orang-orang kafir, dan menjadi pengikut orang kafir. Lantas kemudian orang-orang tersebut berkata, tidak boleh keluar dari kepemimpinan mereka kecuali jika mereka telah kafir! Lalu bagaimana mereka bisa kafir? Orang-orang itu akan berkata, “Pemimpin dikafirkan jika dirinya melakukan kekufuran yang nyata.”
Oleh karena itulah mereka sering berkata, “Pemimpin itu kan masih shalat. Ingat! persoalan janji, persoalan hukum itu tidak masuk dalam persoalan shalat yang dia lakukan! Namun lebih kepada faktor kepemimpinannya, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam bagian yang ketiga—dari segi pelaku yang melakukan akad.
Kita berbicara tentang hukum dan tugas pemimpin yang berhubungan dengan akad yang mengesahkan kepemimpinnannya. Mereka berkata, “Tidak boleh memberontak pemimpin kecuali jika status pribadi mereka telah kafir.” Jadi, meskipun dia membatalkan seluruh janji yang terkait dengan kepemimpinannya, selama dia tidak kafir maka tidak boleh keluar dari ketaatan kepdanya.
Kemudian mereka berkata, bukan hak kita untuk mengafirkan penguasa. Salah satu catatan atas kerancuan berpikir mereka atas sesuatu yang tidak mungkin terjadi: kita tidak boleh mengafirkan pemimpin sampai kita mengetahui isi hatinya, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin kecuali jika dia kafir, kita tidak boleh mengafirkannya sehingga kita bisa memastikan isi hatinya, apakah hatinya mengingkari perbuatan kufurnya atau tidak.
Artinya jika dia melakukan perbuatan kufur akbar dengan perbuatan yang telah disebutkan kafir oleh Allah; seperti berhukum dengan selain hukum Allah, mencela agama Islam seperti menghina sunnah, maka mereka akan berkata, “Pelaku tersebut tidak boleh kita hukumi kafir sehingga kita bisa mengetahui isi hatinya, apakah dia menghalalkan perbuatan tersebut ataukah tidak.”
Maka pada hakikatnya sikap seperti itu sama saja menghilangkan makna hadits Nabi SAW, “Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata.” Tidak mungkin kita menilai sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang nampak saja. Kemudian mengapa kita dituntut atau mereka menuntut umat agar tidak mengafirkan pemimpin atau keluar dari ketaatan kepadanya kecuali setelah dia mengetahui isi hatinya???
Para penguasa itu telah mengetahui permainan ini, mereka melakukan setiap perbuatan kufur—kekufuran yang telah ditetapkan Allah SWT—kemudian dia tampil di depan rakyatnya dan berkata, “Kami bagian dari kaum muslimin.”. Saat itulah (menjadi alasan) tidak boleh keluar dari kepemimpinannya. Sudah sewajarnya jika ada anggapan agama Yahudi, Nasrani dan konsep sekuler dalam berpolitik menjadi lebih mulia dan terhormat daripada agama Islam yang mereka yakini.
Akad yang paling besar dan berkaitan dengan kepentingan Islam adalah menyebarkan agama, menegakkan kebenaran, keadilan dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Inilah janji utama antara pemimpin dan rakyat.
Sehingga dalam hal ini, persoalan utama yang seharusnya ditinjau dari bentuk janji utama tersebut diganti menjadi kepada persoalan pribadi pemimpin. Sementara kita tidak mungkin menghukuminya kecuali setelah mengetahui isi hatinya. Sehingga kita membutuhkan alat deteksi hati yang paling canggih dan tentu alat itu tidak akan ada. Yah, alat untuk mengetahui isi hati, apakah dia menghalalkan sebuah perbuatan atau tidak, apakah dia mencintai Islam atau benci terhadapnya.
Penguasa mengerti bahwa umat ini tidak tahu tentang akad, tidak tahu makna hukum, tidak mengerti hakikat pemimpin. Kondisi seperti ini menjadikan para penguasa bisa dengan leluasa memperlakukan umat yang telah terdokrin dengan pemikiran di atas. Dia akan tampil di hadapan mereka dan berkata, “Kami Ahlus Sunnah, kita beragama Islam, kita mencintai Islam, kita ingin Islam ini bisa berkembang dan meluas.” Setelah itu, selesailah semua urusan!
Maka sangat wajar jika realitas yang terjadi sekarang ini umat Islam menjadi umat yang paling hina, sedangkan thaghut yang paling besar saat ini adalah para pengusa kaum muslimin yang bisa bertindak dengan sekehendaknya sendiri.
Bandingkan dengan negara Barat, apakah ada pemimpin mereka yang bisa bertindak sekehendaknya sendiri seperti halnya para pemimpin di negara kita? Pemimpin yang bisa mengeksploitasi rakyat sehendaknya sendiri dan bebas menzalimi mereka, sementara rakyat tidak mau peduli apa yang dilakukan pemimpinnya, karena mereka tidak boleh mempertanyakan kelakuan para pemimpinnya, selain pertanyaan itu juga berpotensi munculnya kebencian di hati rakyat—hasbunallahu wa ni’mal wakiil.
Sekarang para pemimpin bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, sedangkan kita tidak boleh keluar dari kepemimpinan tersebut sampai dia menjadi kafir. Terus kita tidak boleh mengafirkan mereka sampai kita bisa menelisik isi hati mereka. Sementara itu Nabi SAW bersabda, “Kecuali jika kamu melihat kekufuran yang nyata.” Lantas, bagaimana bisa kita melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, bagaimana kita bisa melihat isi hati seseorang?!
Jadi, kapan kita boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin?
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam hal ini kita harus melihat status akad yang terjalin antara rakyat dan pemimpin dengan benar dan sesuai petunjuk syar’i. Kita harus menilai berdsasrkan petunjuk agama Allah SWT dan jauh dari sikap pengagungan atau pengkultusan terhadap para pemimpin seperti yang telah terjadi hari ini.
Kita harus menjelaskan kepada umat bahwa kewajiban yang dibebankan kepada pemimpin itu adalah sama dengan kewajiban yang dibebankan kepada umat. Akan tetapi umat mengangkatnya sebagai pemimpin agar bisa menuntun mereka untuk merealisasikan kewajiban tersebut. Demikianlah gambaran hubungan yang sebenarnya antara hukum, pemimpin dan yang dipimpin di dalam Islam. Atas dasar itu pula kita juga bisa mengerti kapan seseorang boleh keluar dari ketaatan kepada penguasa.
Kapan Wajibnya Keluar dari Ketaatan terhadap Pemimpin yang Melakukan Kekufuran?
Pertama
Menurut ijmak para ulama, rakyat wajib keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya jika pemimpin tersebut kafir. Maknanya bahwa jika dia melakukan salah satu perbuatan kekufuran, maka rakyat boleh keluar dari kepemimpinannya tanpa harus melihat isi hatinya, tanpa harus melihat niatnya, tanpa harus melihat maksudnya –apakah dia mengingkarinya atau tidak. Namun perintahya adalah, “Kecuali jika kamu melihat kekufuran yang nyata”, yaitu jika pemimpin tersebut melakukan perbuatan kufur, baik perbuatan kufur yang bersifat pribadi seperti menghina agama, menginjak Al-Qur’an atau perbuatan kufur yang berkaitan dengan rakyat.
Kedua
Wajib keluar dari ketaatan kepada pemimpin ketika pemimpin tersebut meninggalkan tugas utama dari kepemimpinan; seperti tugas menegakkan syariat, menegakkan keadilan, menyebarkan Islam dengan syariat jihad fi sabilillah. Apabila seorang pemimpin mengabaikan salah satu dari urasan utama yang dipercayakan umat kepadanya, maka umat tersebut wajib keluar dari kepemimpinannya.
Penerjemah: Fahrudin
0 Comments:
Subscribe to:
Catat Ulasan (Atom)